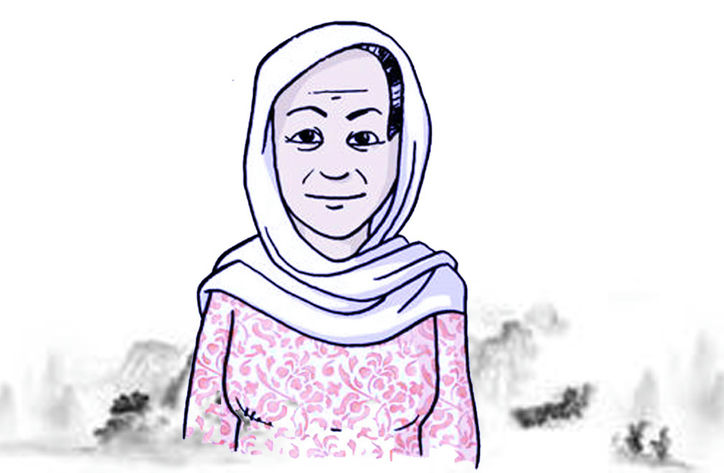SALAH satu yang menjadi tanda bila ibu sedang ada masalah, ialah sakit, meskipun tanda itu tidak sepenuhnya benar. Hal itu melekat pada ibu sejak kapan, aku tidak ingat. Kami—ibu memiliki enam orang anak—tahu apa yang harus kami lakukan. Apalagi jika bukan terus mendesak ibu untuk mengatakan masalah yang sedang menderanya kepada kami, atau menjebak ibu pada sebuah pertanyaan yang membuatnya dapat melontarkan pengakuan.
Sebelum aku mengetahui isi kepala ibu, biasanya aku terlebih dulu mengabari saudara-saudaraku yang tinggal menyebar di berbagai tempat, bahwa ibu sedang bla…bla…. Semua kakakku sudah hidup bersama pasangannya masing-masing, tidak tinggal serumah dengan ibu. Aku sendiri belum memiliki pasangan hidup.
“Mas Mahdi baru saja WA, nanti sore katanya akan datang,” ucapku sembari meletakkan gelas berisi teh hangat yang baru saja ibu minum.
“Ibu tidak tahu lagi, kamu ini tuli atau benar-benar keras kepala? Sudah berapa kali ibu bilang, Fahri? Tidak usah mengabari kakak-kakakmu kalau ibu hanya meriang. Gara-gara kabarmu, mereka selalu jadi repot. Mengorbankan waktu untuk ke sini, padahal sebenarnya ada urusan lain. Atau pasti kalau mereka ke sini, selalu membawakan apa-apa.”
“Mereka berhak tahu keadaan ibu. Mereka juga anak ibu. Aku tidak mungkin menyembunyikannya.”
Terdengar desahan di telingaku. Ibu menatapku dengan wajah kesal. Tapi kutangkap sekilas matanya, mata itu seperti memancarkan kebahagiaan, mata itu seperti menaruh penghargaan terhadapku, atas apa yang kulakukan. Aku tidak pernah yakin ibu benar-benar tidak mengharapkan kehadiran kakak-kakakku saat ia sedang sakit, sebab aku tahu, kala sehat pun, ibu sering memintaku untuk menghubungi salah satu kakakku yang sedang ia rindukan. Jadi kupikir, masalah himbauan ibu agar aku tidak mengabari kakak-kakakku saat ia sedang tidak sehat hanya basa-basi saja—meskipun itu sering dilakukannya.
“Jadi hanya masalah cincin yang dipinjam Yu Siyem?” tanyaku, setelah aku terus menyerang ibu untuk mengungkapkan apa yang ia pikirkan.
Yu Siyem adalah tetangga depan rumah kami. Kata ibu tepat setahun yang lalu, Yu Siyem pinjam cincin kepadanya. Cincin itu Yu Siyem gunakan untuk melunasi utangnya kepada lintah darat yang telah jatuh tempo pelunasan. Yu Siyem memang terkenal sebagai orang yang mudah meminjam uang ke lintah darat, untuk memenuhi keperluan bila ia sedang dalam keadaan terdesak. Ia pernah mempunyai utang hingga beberapa bulan belum ia lunasi. Alhasil bunganya pun membengkak. Tetangga-tetangga heran dengannya, karena Yu Siyem pernah mengemukakan keberatannya mengembalikan utang beserta bunga yang menurutnya sudah cukup berat. Bahkan ia pernah juga mengutarakan hal itu pada anak bungsunya—Yu Siyem memiliki tiga orang anak, dua anaknya yang lain sudah hidup bersama pasangannya masing-masing. Oleh anaknya ia sudah disuruh berhenti berutang ke lintah darat langganannya. Menurut anaknya lintah darat langganannya sudah terlampau kejam. Yu Siyem tetap ngeyel. Kata Yu Siyem, di lintah darat langganannya tidak melewati prosedur yang ribet saat mau berutang.
Ibu suka menolong orang lain, termasuk menolong orang yang dalam keadaan terdesak akan meminjam uang atau barang berharga dalam bentuk apapun padanya. Ibu pasti akan memberikan pinjaman bila sedang ada, tanpa pernah mengambil keuntungan, tanpa pernah menagih-nagih. Begitu pun dengan almarhum bapak. Ia begitu entengnya memberi utangan kepada orang lain saat ia ditembusi perihal itu, tanpa khawatir bila tidak bisa mengembalikannya atau bablas dibawa pergi.
Aku tidak tahu, apa yang membuat ibu memikirkan utang Yu Siyem padanya. Seumur-umur baru kali ini, ibu peduli dengan utang.
“Apa sudah lewat kesepakatan pelunasan?” Selidikku.
“Ibu tidak pernah membuat kesepakatan dengan Yu Siyem, Ri.”
“Lalu?”
“Ya, tidak pakai lalu. Pokoknya ibu menginginkan sesegera mungkin, Yu Siyem membayar utang cincinnya, untuk keperluan. Nanti sore atau besok tolong, kamu datang ke tempat Yu Siyem, tagihkan utangnya dengan kata-kata yang halus. Kalau memang belum ada, ya sudah tidak apa-apa,” ucap ibu.
“Keperluan apa? Apa ibu benar-benar sedang tidak ada uang? Atau ibu membutuhkan uang dalam jumlah yang besar, sampai-sampai menyuruhku menagih? Kalau hanya sedikit aku punya, Bu.”
“Sudah, tidak usah banyak ingin tahu. Penuhi saja permintaan ibumu ini, Ri.”
Sorenya aku ke rumah Yu Siyem. Sebelum itu, tempurung kepalaku benar-benar diisi rasa penasaran ; ujaran ibu tentang keperluan yang belum terjelaskan. Aku terus menerka-nerka, ibu sedang mempunyai keperluan apa? Tapi setelah terus kuterka, aku tidak menemukan kesimpulan apa-apa. Tidak kutemukan tanda-tanda yang mengarah ke sana.
Pendengaranku menangkap suara mesin jahit. Yu Siyem sudah jelas sedang menjahit. Tidak ada orang lain di rumah itu selain dirinya. Gelar janda sudah melekat padanya, ia ditinggal mati suaminya. Anak bungsunya belum pulang dari kerja. Hari-hari Yu Siyem hanya disibukkan dengan mesin jahit, atau menanam padi di sawah milik orang bersama teman-temannya.
“Sudah kukembalikan, Ri. Aku serahkan ke kakakmu, si Mahdi, sebulan yang lalu. Waktu itu dia ke rumahku memberi durian, bersama istrinya. Katanya anaknya yang sulung baru saja pulang menengoknya, dan membawa durian. Katanya juga ibumu diberi. Pada saat aku serahkan uangnya, kata dia akan memberikan ke ibumu.”
“Uang? Bukannya Yu Siyem utangnya cincin?” Aku jelas terkejut mendengar kalimat terakhir yang terlontar dari mulut Yu Siyem.
“Iya, cincin itu dulu aku jual. Laku satu juta lima ratus. Maka aku serahkan uang satu juta lima ratus kepada si Mahdi. Toh, nilainya sama. Berarti Mahdi belum memberikannya ke ibumu. Buktinya kamu ke sini.”
Aku tidak menanggapi kata-kata Yu Siyem. Dalam sekejap aku merasa malu dan menganggap lucu Yu Siyem. Aku malu, dan merasa kecelik sebab utang Yu Siyem ternyata sudah dibayar. Lucu? Mestinya Yu Siyem tidak mengembalikan utangnya dalam wujud uang. Sadar atau tidak sadar, Yu Siyem sudah licik. Tentu, utang yang ia kembalikan tidak sebanding jika ia mengembalikan dalam bentuk cincin. Harga emas semakin hari semakin naik. Utang yang ia kembalikan dalam bentuk uang itu jelas tidak cukup bila dibelikan cincin seberat yang ia pinjam dulu dari ibu. Aku ingin protes. Namun kurasa aku kurang pantas ikut campur dalam urusan ini. Aku lebih memilih pulang.
Aku mengutuk Mas Mahdi! Tindakannya kuanggap sudah kurang ajar. Di antara kakak-kakakku yang lain, kakakku yang satu ini paling banyak membuat masalah di keluarga kami.
Mas Mahdi-lah yang membuat bapak harus mencicipi kebangkrutan, dan membuat roda kehidupan keluarga kami berada di bawah, seperti tidak berputar. Ia sering bolos sekolah pada masa remaja. Ia kerap main tangan saat ia dikecewakan kakak-kakakku yang lain, bahkan aku. Pernah aku dipukulnya sampai sekitar mataku sebelah kanan berwarna biru, hanya gara-gara aku pulang sore karena bermain bersama teman-teman. Ibuku menyuruh Mas Mahdi mencariku dan menyuruhku untuk pulang. Mas Mahdi jengkel, aku dianggapnya telah menciptakan pekerjaan untuknya, sehingga ia melampiaskan kejengkelannya padaku.
Tiba di rumah, Mas Mahdi sudah datang. Sepeda motornya berwarna biru terparkir di depan rumah. Aku mendengar suara kecipak air. Aku kembali teringat percakapanku dengan Yu Siyem di rumahnya, aku sungguh merasa malu. Aku menagih utang dengan tujuan agar ibu lekas sembuh, dan sampai di tempat yang memiliki utang, aku harus dihadapkan pada sesuatu yang tidak pernah kuduga. Rasanya ada yang mendesak-desak ingin keluar dari balik dadaku.
“Bagaimana, Ri?” tanya ibu kepadaku.
“Tanya saja sama Mas Mahdi,” ucapku sedikit emosi.
“Kok Mas Mahdi?”
“Ya, hanya dia yang tahu semuanya.”
“Ada apa ini?” Tiba-tiba Mas Mahdi sudah berdiri di pintu kamar, mengelap kepalanya yang basah dengan handuk.
“Uang yang diberikan Yu Siyem kepada Mas Mahdi sebagai pelunasannya atas utang cincin kepada ibu mana, Mas? Mas Mahdi kan yang dipasrahi?”
“Uang? Dari Yu Siyem? Aku tidak menerima apa-apa…”
Jejak Imaji, 2020
 Risen Dhawuh Abdullah, lahir di Sleman, 29 September 1998. Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan (UAD) angkatan 2017. Bukunya yang sudah terbit berupa kumpulan cerpen berjudul Aku Memakan Pohon Mangga (Gambang Bukubudaya, 2018). Alumni Bengkel Bahasa dan Sastra Bantul 2015, kelas cerpen. Anggota Komunitas Jejak Imaji dan Luar Ruang. Bermukim di Bantul, Yogyakarta.
Risen Dhawuh Abdullah, lahir di Sleman, 29 September 1998. Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan (UAD) angkatan 2017. Bukunya yang sudah terbit berupa kumpulan cerpen berjudul Aku Memakan Pohon Mangga (Gambang Bukubudaya, 2018). Alumni Bengkel Bahasa dan Sastra Bantul 2015, kelas cerpen. Anggota Komunitas Jejak Imaji dan Luar Ruang. Bermukim di Bantul, Yogyakarta.
Baca : Malam Masih Panjang, dan Kalian akan Merasa Lapar