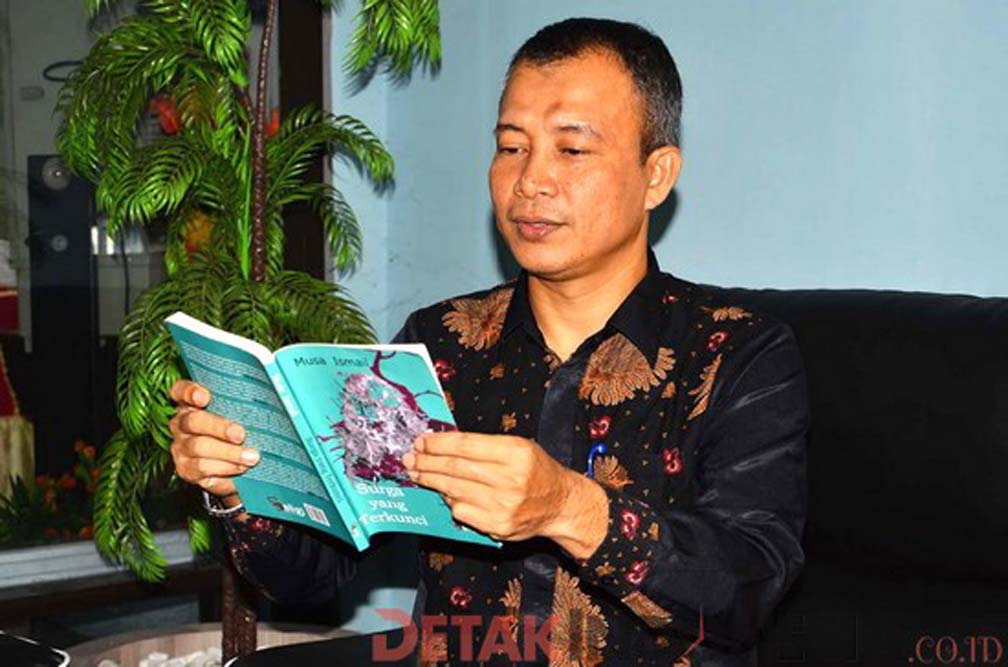Oleh Musa Ismail
INGAT kasus viral Pertamina, ingat pula tema-tema korupsi dalam karya sastra dengan beragam topiknya. Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya, merupakan isu yang telah lama menjadi bidikan sastrawan Indonesia. Beragam karya sastra lahir dari topik yang sedang meledak ini. Sejumlah novel seperti Korupsi (Pramoedya Ananta Toer, 1954), Orang-orang Proyek (Ahmad Tohari, 2002), dan Republik Tikus (Hardi S. Moeis, 2003) turut menggambarkan dampak destruktif dari praktik korupsi terhadap individu maupun masyarakat. Dengan membandingkan Ladang Perminus dengan karya-karya tersebut, kita dapat melihat bagaimana berbagai aspek korupsi telah dikritik dalam dunia sastra Indonesia. Novel Ladang Perminus (Perminus = Perminyakan Nusantara) karya Ramadhan KH (1975) menyajikan kritik sosial terhadap praktik korupsi dalam industri minyak. Kritik sosial ini disuguhkan melalui kisah seorang insinyur muda yang berusaha mempertahankan idealismenya di tengah sistem yang sudah kusut. Dengan gaya penceritaan yang lugas, novel ini tidak hanya menghadirkan konflik moral individu, tetapi juga menggambarkan ketimpangan sosial akibat eksploitasi sumber daya oleh segelintir elite korup.
Novel Ladang Perminus menyoroti bagaimana korupsi bukan sekadar tindakan individu, melainkan telah menjadi barah dalam sistem birokrasi dan dunia bisnis. Sastro, tokoh utama dalam novel, mengalami benturan moral saat ia menyaksikan berbagai bentuk penyimpangan di perusahaan minyak Perminus. Dalam novel ini, para pejabat dan pengusaha lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat. Bukankah ini masih kuat relevansinya dengan kondisi terkini?
Fenomena yang digambarkan dalam Ladang Perminus relevan dengan kondisi nyata di Indonesia. Sektor minyak dan gas sering kali menjadi lahan praktik korupsi. Transparency International (2023) menyebutkan bahwa industri ekstraktif, termasuk minyak dan gas, merupakan salah satu sektor dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Pada 2022, ICW mencatat di Indonesia, berbagai kasus seperti skandal Pertamina di era Orde Baru dan kasus korupsi impor minyak menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya alam masih menghadapi tantangan besar.
Persoalan serupa juga muncul dalam novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari (2002), yang menyoroti korupsi dalam proyek pembangunan. Tokoh utamanya, seorang insinyur proyek, menghadapi tekanan dari sistem yang telah terbiasa dengan praktik suap dan penggelapan dana. Sama seperti Sastro dalam Ladang Perminus, tokoh utama dalam Orang-orang Proyek juga harus menghadapi dilema moral antara bertahan dengan idealismenya atau mengikuti arus korupsi yang sudah mengakar.
Konflik yang dialami Sastro mencerminkan dilema moral yang dihadapi oleh banyak individu dalam sistem yang telah terkontaminasi oleh sistem yang korup. Ia ingin menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas, tetapi tekanan dan intervensi dari lingkungan yang membuatnya harus mempertimbangkan karier dan keselamatannya sendiri. Dilema ini menggambarkan betapa sulitnya mempertahankan idealisme dalam situasi di mana ketidakjujuran telah menjadi norma. Idealisme yang rapuh bisa berkecai seketika ketika berhadapan dengan kondisi ini.
Dalam Korupsi karya Pramoedya Ananta Toer (1954), tokoh utama Bakir mengalami dilema serupa. Sebagai pegawai negeri. Bakir awalnya berpegang teguh pada kejujuran, tetapi akhirnya tergoda oleh kekayaan yang bisa diperoleh melalui praktik korupsi. Berbeda dengan Sastro yang tetap berusaha menjaga idealismenya, Bakir akhirnya jatuh dalam lingkaran korupsi, yang kemudian menghancurkan hidupnya. Kedua novel ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga ujian moral bagi individu yang hidup dalam barah sistem yang bernanah berdarah.
Selain membahas korupsi di tingkat perusahaan dan pemerintahan, karya sastra tersebut juga menyoroti dampak eksploitasi sumber daya terhadap rakyat kecil. Kekayaan minyak yang seharusnya menjadi milik bangsa justru hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sementara itu, masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi tetap hidup dalam kesulitan.
Fenomena ini juga tergambar dalam Republik Tikus karya Hardi S. Moeis (2003), yang menggunakan metafora “tikus” untuk menggambarkan para pejabat dan pengusaha yang terus menggerogoti kekayaan negara. Novel ini menampilkan gambaran birokrasi yang penuh dengan praktik korupsi. Kepentingan rakyat sering kali diabaikan demi keuntungan pribadi. Novel ini juga menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi sistemik dan sulit diberantas karena adanya hubungan erat antara politisi dan pengusaha. Korupsi seumpama benang kusut yang sulit diuraikan.
Pada 2023, Tempo mencatat bahwa banyak daerah penghasil minyak di Indonesia seperti Riau dan Kalimantan, masyarakat setempat sering kali tidak merasakan manfaat dari kekayaan alam yang dieksploitasi di wilayah mereka. Infrastruktur yang kurang memadai dan kesejahteraan masyarakat yang tertinggal menjadi bukti bahwa hasil eksploitasi minyak lebih banyak menguntungkan elite ekonomi dan politik dibandingkan rakyat biasa.
Karya sastra tersebut menyuguhkan beragam konflik yang mencerminkan realitas penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam beragam sektor. Konflik utama dalam novel ini terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, konflik individu versus sistem. Kedua, konflik sosial: elit korup versus rakyat biasa. Konflik ini menggambarkan ketimpangan sosial yang terjadi akibat sistem yang tidak adil, di mana kekayaan negara justru dinikmati oleh segelintir orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Ketiga, konflik internal yang berkaitan dengan dilema moral. Adanya pergulatan batin tokoh karena harus memilih antara mempertahankan nilai-nilai kejujurannya atau menyerah pada tekanan lingkungan. Konflik batin ini menjadi salah satu aspek menarik dalam novel karena mencerminkan dilema yang sering dihadapi oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan yang sakit. Keempat, konflik politik dan ekonomi. Novel ini juga menampilkan bagaimana korupsi dalam berbagai kasus tidak hanya melibatkan perusahaan, tetapi juga pejabat pemerintahan yang berkolusi dengan pengusaha. Hubungan erat antara dunia politik dan bisnis menyebabkan kebijakan yang seharusnya menguntungkan rakyat malah digunakan untuk kepentingan pribadi.
Beberapa novel tersebut merupakan kritik pedas terhadap korupsi di berbaga sektor yang masih menjadi persoalan di Indonesia hingga saat ini. Begitulah sastrawan.Dia mampu menyoroti ketimpangan yang sudah menjadi penyakit yang menyakitkan rakyat. Sebagai refleksi sosial, novel-novel ini mengajarkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari reformasi sistemik, penguatan integritas individu, serta pengawasan ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, sumber daya yang seharusnya menjadi milik rakyat benar-benar dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. ***