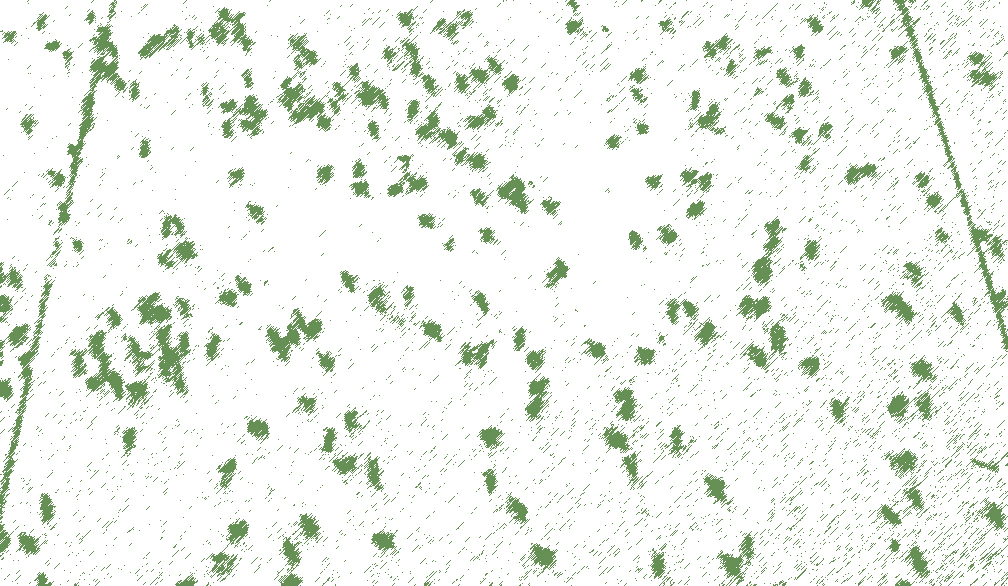BILA musim lalat tiba, Rina akan kangen bunda. Ia sudah lupa berapa bulan bunda meninggalkan dirinya. Bunda tidak bilang akan pergi kemana, juga tidak memberi tahu alasannya. Yang ia ingat, bunda hanya pamit membeli sayur. Lalu keesokan hari, bunda tidak lagi di rumah. Padahal setiap musim lalat, ia dan bunda akan menangkap lalat dengan berbagai macam cara. Untuk kemudian dipenyek dengan sapu lidi atau sandal jepit. Bagi bunda, tidak ada ampun bagi siapa saja yang membawa racun ke rumah. Ucapan bunda itu, terkubur dalam di benak Rina.
Jika tidak salah hitung, enam hari sudah lalat mengeriap di lantai dapur, ruang tamu, teras, kursi tamu, jendela, halaman, dan entah tempat-tempat mana lagi. Lalat-lalat itu berkeliaran bebas, terbang kesana-kemari tanpa peduli apa-apa. Yang lebih parah, ketika lalat berwana hijau datang, meski dalam jumlah sedikit—membawa denging keras—mematikan rasa selera makan.
“Andai ada bunda, lalat-lalat ini tidak akan sebanyak ini,” sesalnya sambil mengingat gerakan bunda memenyek lalat di teras rumah.
Rina tahu apa yang dibawa lalat besar warna hijau, karena terkadang di sela-sela menangkap lalat, bunda menyisipkan certia perihal lalat hijau. Ia geli memandangnya, makan pun tak begitu ennek.
“Lalat hijau terlalu jorok untuk tidak dibunuh,” dalam kamar yang pengap, bunda bercerita.
“Kenapa Bun, kenapa hanya lalat hijau yang harus dibunuh duluan,” wajah lucu itu begitu menyejukkan hati bunda.
“Pokoknya harus dibunuh duluan, dan jangan sampai menyentuh makanan yang akan Rina makan. Karena lalat hijau sangat menyukai kotoran yang baunya menyengat.” Rina mengangguk sambil memoncongkan kedua bibirnya.
“Ooo… begitu bunda,” sambung Rina kemudian memasang wajah polos.
Semenjak saat itu Rina paham, jika ada lalat hijau yang nongkrong di teras atau dimana saja yang Rina ketahui, harus cepat-cepat dibunuh, baru kemudian lalat warna keabu-abuan menyusul, nyaris sama seperti yang bunda lakukan. Tapi saat ini, ia tidak begitu selera. Ayunan tangannya tidak segesit bunda. Jelur-jelir saat mengikuti gerakan lalat tidak sepiawai perempuan yang dirindu sekarang.
Pernah suatu sore ketika Rina sendang makan roti di teras rumah sendirian. Lalat hijau tiba-tiba berdenging dan hinggap begitu saja di bekas gigitan rotinya. Spontan Rina membuang dan mengincar lalat hijau kemanapun pergi, bila tidak mati, sedikitpun tak ada ampun baginya.
“Bunda, ada lalat hijau yang hinggap di roti Rina,” teriak Rina dari amperan rumah.
Bunda yang mendengar langsung lari kecil menuju Rina sambil memegang sapu lidi sebagai alat membunuh. Tatapan bunda nyalang menyoroti tempat lalat hijau hinggap. Rina mengakui, bila penglihatan bunda mengunci mangsa, maka tidak ada kata selamat. Meski dirinya tidak tahu dari mana bunda belajar membunuh sehebat itu. Tapi menurut bunda, ayah lebih gesit dan hebat lagi dalam membunuh.
“Rotinya mana, Nak?” tanya bunda ketika sampai di hadapan Rina.
“Sudah Rina buang, Bun. Itu lalat hijaunya,” telunjuk Rina mengarah pada lalat hijau yang nangkring di kotoran ayam basah. Rina bergidik dan seketika pula bulu di tangan menggeriap. Sesuatu entah, tiba-tiba membuat isi perutnya melonjak ke atas.
Bunda maju pelan-pelan sambil mengangkat sapu lidi tinggi-tinggi. Rina diam tidak membuntuti, takut lalat hijau merasa terganggu dan hinggap di kulitnya. Kaki telanjang bunda semakin pelan, diikuti sapu lidi yang meninggi. Urat hijau di tangan bunda perlahan tampak. Dan tanpa hitungan, bunda langsung memukul lalat hijau yang sama sekali tidak merasa terusik.
Setelah sapu lidi diangkat, lalat hijau penyek bercampur dengan kotoran ayam yang nyaris menyerupai ampas kopi basah. Lagi-lagi Rina bergidik serasa isi perut ingin keluar lebih cepat tatkala bau kotoran ayam menyeruak ke segala arah.
“Jangan dilihat,” pinta bunda cepat.
Dalam hati, Rina membatin, “Terlambat, Bun, Rina kadung melihat.” Cepat-cepat Rina pura-pura tidak melihat. Bunda pun memicing-micingkan mata, lalu menghampiri Rina tanpa rasa bersalah.
“Rotinya jangan diambil, sudah kasikkan ke ayam,” yang kesekian kali bunda menyuruh Rina untuk membuang rotinya.
Rina mengangguk samar, merespon apa yang bunda ucapkan. Dalam tempurung kepalanya, Rina berpikir. Jika lalat hijau membawa penyakit, kenapa roti yang dihinggapi lalat tadi harus dikasikkan ke ayam. Bukankah nati ayamnya juga akan sakit?
Rina urung melaksanakan perintah bunda. Ia lebih memilih menguburkan roti itu supaya ayam-ayam sehat seperti bunda dan dirinya. Ia tidak ingin kehilangan suara-suara ayam, sama seperti tidak inginnya kehilangan panggilan ayah sewaktu ia kecil.
Setelah itu, bunda membasuh sapu lidinya untuk kemudian digunakan membunuh lalat-lalat lain yang lebih kecil. Bagi sapu lidi bunda, tidak ada ampun pada lalat-lalat yang berani hinggap di rumah. Bunda sudah kadung trauma. Kata bunda, ketika melihat tumpukan lalat begitu banyak, kenangan yang teramat menyedihkan itu seketika tergambar jelas di kepalanya. Seakan terjadi untuk yang kesekian kali.
Begitulah yang akan Rina lakukan ketika bunda ada di rumah. Begitu kangen Rina masa-masa seperti itu, dimana bunda begitu memprioritaskan kesehatan dirinya. Kapan bunda pulang? Harapnya berselubung cemas.
Saat ini, semenjak kepergian bunda yang tidak tahu kemana, Rina dititpkan ke nenek yang tidak begitu bisa bergerak leluasa. Sendi-sendinya tidak bisa berfungsi normal. Keriput yang sangat tampak itu mengisyaratkan bahwa bicara nenek tidak mudah dicerna.
Untung saja nenek selalu punya cerita-cerita menarik perihal keluarganya. Meski bicara nenek tidak bisa ia cerna sempurna, mengulang kata yang sama kerap kali ia lakukan. Banyak hal yang nenek ceritakan ketika sudah kadung bercerita. Mulai dari ayah Rina yang dulu begitu malu-malu saat bertemu dengan nenek. Dan amat gerogi ketika berhadapan dengan kakek. Setiap mendengar cerita keusilan kakek-nenek, bibir mungil Rina serasa tidak bisa mingkem rapat-rapat. Selalu ingin tersenyum dan tertawa pelan-pelan tanpa keluar suara.
“Kapan kakek yang meninggal, Nek?” tanya Rina seketika.
Nenek terkesima mendengar pertanyaan sang cucuk. “Kakek meninggal lama sudah,” dengan sisa suara yang bisa nenek kerahkan, sang nenek menjawab meyakinkan.
Rina hanya mangut-mangut seolah paham kapan waktu itu terjadi; kematian kakek. Tetapi jawaban nenek tidak lantas membuat ia berhenti bertanya. Rasa ingin tahu dalam tempurung kepalanya tidak bisa ia tahan lebih lama lagi. Serba tanya menggantung begitu saja, jika tidak diutarakan, barangkali hal itu menjadi sesal dikemudian. Hidup tanpa tanya, serupa kopi tanpa gula.
“Memangnya, kakek meninggal karena apa, Nek?”
“Kakek meninggal karena nasi bungkus sebelum dimakan ada tujuh lalat hijau yang tiba-tiba hingga di nasi bukus kakek yang sudah dibuka. Waktu itu kakek hanya mengusir lalu memakan seolah tidak ada apa-apa.” Suara nenek berat seketika, seperti ada sesuatu yang berat menarik kuat-kuat.
Sontak Rina terkejut dengan apa yang diutarakan nenek. Benarkah kakek meninggal karena tujuh lalat hijau yang hinggap di nasi bungkus itu? Kenapa bisa tujuh ekor lalat hijau? Ada apa dengan nasi bungkus kakek, kok sampai dihinggapi lalat hijau sebanyak itu? Pertanyaan-pertanyaan ganjil berkelindan dalam kepalanya.
“Mengapa begitu, Nek?”
“Karena selain lalat hijau menyukai bau-bau yang menyengat, lalat hijau juga peka terhadap bau racun,” mata nenek tampak membeling. Dadanya seakan sesak. Tangan sepuh itu memegang dada ringkihnya menahan perih yang amat mendera.
Rina memilih diam, tidak menyahut, pun tidak bertanya lagi. Ia lebih memikirkan kenapa nasi kakek bisa ada racunnya. Apakah waktu itu—bunda menyuruh membuang roti Rina karena dihinggapi lalat hijau—roti yang dimakannya terdapat racun? Ia tidak begitu dalam memikirkan hal tersebut. Lagian itu hanya satu lalat, bukan tujuh lalat seperti yang nenek ceritakan
Perlahan Rina mulai paham bahwa lalat hijau bisa jadi musibah, bisa pula pula berkah, tergantung apa yang terjadi di lapangan. Meski begitu, ia tidak boleh terlalu berlarut-larut memikirkan keterpurukan di masa lalu. Terutama perihal keluarga yang ia tidak tahu tuntas.
“Apa tubuh kakek dikerubungi lalat hijau, Nek?” setelah sekian menit membisu, kembali Rina mencoba bertanya.
“Tidak juga, karena tubuh kakek, cepat-cepat nenek tutup dengan sampir,” dengan mata yang membeling nenek menjawab.
“Apa setelah kakek dikuburkan, pelaku yang meracuni kakek ditemukan, Nek?”
“Beberapa hari kemudian tidak kunjung temu. Akan tetapi, ketika genap tiga bulan, orang yang meracuni kekek ditemukan.”
“Siapa orang yang meracuni kakek, Nek?” sanggah Rina cepat setelah nenek selesai berbicara.
Nenek tidak langsung menjawab, hanya menarik nafas sambil nanar manatap wajah Rina yang semestinya tidak mendengar cerita kematian keluarga.
“Yang meracuni kakek…,” begitu saja nenek memotong kalimatnya. Rina begitu sigap mendengar kelanjutan ceritanya. “Ayah Rina!”
Hening seketika. Desir angin yang sejuk berubah menjadi hangat. Gerisik daun siwalan terdengar begitu pelan dari lorong sana. Dalam kepala, tak ada kata-kata yang bisa diutarakan. Untuk bertanya mengapa ayah tega meracuni kakek? Apa musababnya? Sedikitpun tidak terbesit dalam kepala kanak-kanaknya.
Ia tidak bisa harus bertanya apa lagi perihal kematian kakek. Semuanya jelas, sangat jelas. Mengapa bunda tidak cerita perihal kematian ayah? Apakah kematian ayah karena…? Ia tidak mau berpikiran buruk tentang nenek. Mungkin bunda…? Ia tidak akan berpikir bahwa nenek yang membunuh ayah. Tapi seperti yang dilihat di tivi-tivi, banyak orang dekat yang membunuh orang dekat.
Dalam suasana yang mengaharukan, Rina tidak bisa menguasai perasaan kecilnya. Ia kalah dan memilih menjatuhkan air mata. Nenek yang melihat tidak kuasa menampung kesedihan yang harus Rina tanggung. Seketika saja, dalam hitungan tahun kala itu, Rina harus kehilangan orang yang terpenting dalam keluarga; ayah dan kakek.
“Tetapi, ayah Rina ditemukan mati dan dikerubungi lalat hijau di dekat sungai ajung perbatasan desa sana,” nenek melanjutkan, mencoba menghibur Rina yang terlanjur sedih.
Purna sudah sesal di dadanya. Begitu rumit keluarga yang menurut Rina—sebelum mengetahui cerita yang sebenarnya—sangat harmonis, yang setiap hari dibumbui tawa, canda-bahagia yang tiada henti saban hari. Ia tidak menyangka, bahwa semua yang telah Rina terima; canda, tawa dan bahagia, hanya menutupi keterpurukan keluarga di masa lalu yang begitu mengenaskan.
“Rina kangen bunda, Nek,” begitu saja Rina mengubah topik pembicaraan.
Nenek tidak langsung menjawab. Ia lebih memilih diam dan mengusap air mata sang cucu sambil menarik tubuh kecil itu untuk dirangkul. Di saat seperti ini, tidak ada sesiapa yang bisa menghangatkan tubuh kecil Rina. Ia begitu tenang dipeluk nenek. Meski rasa hangat tentu beda dari pelukan bunda.
“Kata Buk Ripah, bunda Rina akan datang besok,” begitu sakit nenek berucap demikian. Ia tahu persis apa yang diceritakan Buk Ripah kepada dirinya. Pertama mendengar, begitu terkejut ketika mendengar kabar tersebut. Demi sang suami, ia tidak tahu harus membalas seperti apa?
“Benarkah itu, Nek?” tiba-tiba saja Rina keluar dari pelukan nenek.
Nenek mengangguk mantap dengan sesak dada yang teramat berat. Dan itu tidak mungkin ia utarakan pada cucunya. Karena ia tahu, air mata bening Rina akan mengucur deras.
Anggukan nenek langsung membuat Rina berpikir seketika, ketika bunda tiba di rumah, ia akan begitu kuat memeluknya dan menceritakan apa yang telah diceritakan sang nenek, supaya dirinya tahu kenapa ayah tega meracuni kakek.
Pagi tiba. Suara burung hantu di genting sejak tadi subuh sudah pindah. Burung hantu itu memang biasa hinggap di genting rumah. Lalat-lalat semakin menggeriak-geriak di teras dan halaman saat matahari di timur—seolah sedang menemukan bau yang sangat menyengat.
“Buk Ripah bilang, bunda Rina menaiki mobil warna putih,” ucap nenek ketika berada di teras bersama cucunya.
Rina jauh menatap nanar ke ujung jalan. Lorong begitu sepi, tidak ada hilir mudik sepeda ataupun mobil. Belum sempat Rina bertanya jam berapa. Mobil itu datang. Sekonyong-konyong mobil berwarna putih tiba-tiba masuk ke halaman. Dada Rina pongah seketika; bahagia. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa itu. Mata sembabnya tidak bisa membohongi kalau air matanya memaksa keluar.
Ketika mobil di parkir di halaman. Mata Rina terbelalak dengan pemandangan yang begitu aneh. Mobil itu dipenuhi lalat, begitu banyak sampai tidak terhitung jumlahnya. Lalat kecil dan lalat hijau tidak terhitung jumlahnya. Rasa bahagia yang menyelimuti begitu saja tanggal di lubuk hati Rina.
Dari dalam mobil, Buk Ripah keluar sambil memasang mimik kusut kain kafan. Rina tidak mengerti. Lebih tepatnya, ia bingung apa yang terjadi. Rina menoleh ke wajah nenek. Begitu cepat air mata jatuh dari kelopak keriput nenek. Ia semakin bingung, mobil putih dikerubungi lalat, apa gerangan dalam mobil?
“Apa yang terjadi, Nek?” dalam kebingungan yang akut, Rina bertanya.
Nenek tidak menjawab. Buk Ripah hanya menunduk.
“Silakan dikeluarkan, Mas,” pinta Buk Ripah kepada laki-laki yang tak lain adalah sopir.
Rina berjalan mendekati mobil. Begitu pelan ia melangkahkan kakinya. Tepat di belakang mobil, adan ranjang diturunkan. Seseorang terbaring ditutup dengan kain putih bersih yang kain-kainnya dipenuhi lalat. Rina membuka ujung lurus kepala. Tangisnya pecah seketika. Semua persendiannya lemas. Tatapannya rabun berair. Sesegukan tiba-tiba menerkam dada.
Samar-samar Rina mendengar percakapan nenek dan Buk Ripah.
“Racun lalat itu benar ampuh. Dapat darimana, Nek?”
“Milik menantu yang kusimpan.”
Telinga Rina seketika panas. Dalam emosi yang meluap-luap, terbesit di benaknya, kematian yang disengaja harus dibalas dengan sengaja. ***
Annuqayah Lubangsa, Oktober 2022
———————–
 Muhtadi.ZL, kelahiran Gedangan, Sukogidri, Ledekombo, Jember, Jawa Timur pada September 2000. Kini, mengabdikan diri di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur. Tulisannya berupa, esai, resensi, dan cerpen termuat di pelbagai media offline dan online. Aktif di Komunitas Cinta Nulis (KCN)-Lubsel, Komunitas Penulis Kreatif (KPK)-Iksaj, Lesehan Pojok Sastra (LPS)-Lubangsa. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat menghubungi email: [email protected] dan Whatsapp: 087801000270. *
Muhtadi.ZL, kelahiran Gedangan, Sukogidri, Ledekombo, Jember, Jawa Timur pada September 2000. Kini, mengabdikan diri di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur. Tulisannya berupa, esai, resensi, dan cerpen termuat di pelbagai media offline dan online. Aktif di Komunitas Cinta Nulis (KCN)-Lubsel, Komunitas Penulis Kreatif (KPK)-Iksaj, Lesehan Pojok Sastra (LPS)-Lubangsa. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat menghubungi email: [email protected] dan Whatsapp: 087801000270. *
Baca: Cerpen Djunaedi Tjunti Agus: Puasa